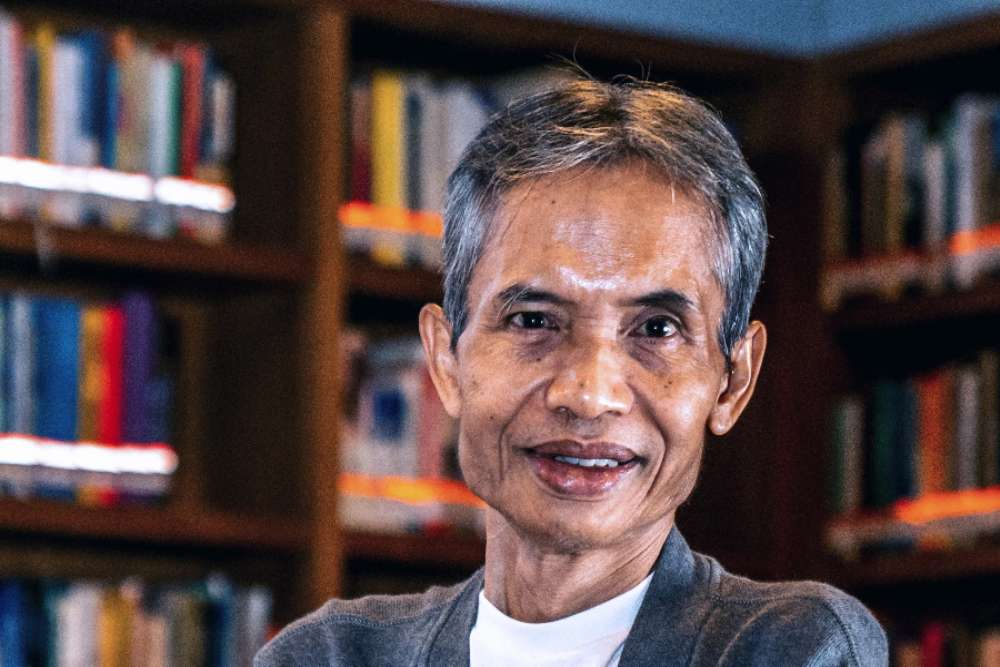Advertisement
WAWANCARA: Mencegah Eks Koruptor Ikut Pemilu
 Titi Anggraini - Perspektif Baru
Titi Anggraini - Perspektif Baru
Advertisement
Salam Perspektif Baru.
Tamu kali ini adalah Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Titi Anggraini mengatakan pelaksanaan pemilu membaik secara prosedural. Namun, hasil pemilu belum berkontribusi terhadap ekspektasi publik, misalnya terhadap peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu Indonesia juga masih mempunyai masalah dengan kualitas kandidat. Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Titi Anggraini.
Advertisement
Apa sebenarnya yang menjadi tantangan dan kecemasan dalam menghadapi pilkada dan Pilpres?
Pada tahun ini, 2018, disebut oleh banyak orang sebagai tahun politik karena ada agenda besar yang akan berlangsung, sudah berlangsung, dan akan terus berlangsung sampai 2019. Di 2018 ada 171 daerah menggelar pilkada yang meliputi 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.
Apakah jumlah itu paling banyak selama dalam sejarah pilkada serentak?
Paling banyak terjadi pada 2015, yaitu ada 269 daerah. Jadi kita secara berkala sedang menata pilkada di Indonesia, sehingga pada 2024 kita akan pilkada serentak seluruh daerah secara nasional dari Sabang sampai Marauke. Jadi sekarang sudah pilkada serentak gelombang ketiga. Gelombang pertama pada 2015, gelombang kedua pada 2017 yang ada harubiru di Pilkada DKI Jakarta, dan pada 2018 merupakan gelombang ketiga.
Kita patut cemas dan mempersiapkan diri sekarang karena pada 2018 jumlah total pemilih di 171 daerah ada 160 juta lebih. Artinya, setara dengan 80% total pemilih seluruh Indonesia kalau kita melaksanakan pemilu legislatif. Pada Pemilu legislatif 2014, jumlah pemilih kurang lebih 187 juta, pada 2018 jumlah pemilih pilkada ada 160 juta. Ini kemudian sangat strategis sebab pada 2019 kita akan melaksanakan Pemilu serentak satu hari, secara bersamaan memilih anggota legislatif dan Presiden untuk petama kali dalam sejarah elektoral Indonesia.
Seharusnya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan karena ini merupakan sesuatu yang baru bagi proses demokrasi kita. Namun tadi Anda mengatakan bahwa ada yang perlu dicemaskan. Apa sebenarnya yang perlu dicemaskan?
Ada beberapa hal yang membuat kita harus mempersiapkan diri karena dengan kecemasan itulah yang akan membuat kita bersiap untuk mengantisipasi. Kita mempunyai pengalaman Pilkada Jakarta yang harus kita akui sudah mengharu-birukan Indonesia.
Pilkada DKI Jakarta berkontribusi terhadap penurunan indeks demokrasi Indonesia. The Economist pada 2017 membuat tagline Minority in Crisis. Krisis minoritas menurunkan skor Indonesia lebih dari 20 poin. Jadi begitu besar kontribusi dari Pilkada Jakarta dalam pandangan internasional. Indonesia dan India adalah dua negara di Asia yang mengalami penuruanan indeks demokarasi global.
Apa yang membuat turun drastis?
Salah satunya kalau memegang angle minoritas dalam krisis artinya ada persoalan. Demokrasi seharusnya inklusif, menjamin kesetaraan, jauh dari intimidasi dan kekerasan. Namun The Economist memotret bahwa ada situasi ketika Pilkada DKI Jakarta orang tidak bisa mengekspresikan pilihannya dengan leluasa. Kemudian minoritas mendapat tekanan ketika dia berbenturan dengan mayoritas, dan itu menjadi warning. Jadi DKI Jakarta betul-betul harus menjadi peringatan bagi kita untuk mengantisipasi ke depan tidak boleh ada lagi peristiwa seperti di DKI Jakarta.
Anda mengatakan bahwa nilai indeks demokrasi kita turun drastis sebagai akibat review dari Pilkada DKI Jakarta. Apakah potensi ini akan terjadi juga di Pilkada serentak tahun ini?
Kalau dilihat dari tensinya, pilkada serentak 2018 cenderung lebih baik dibandingkan 2017. Pada 2017 DKI menjadi sentral karena di DKI berkumpul semua instrumen untuk mendukung itu seperti media, pusat perhatian politik Nusantara, termasuk juga kontestasi yang sangat sengit. Satu-satunya pilkada yang dua putaran itu hanya DKI.
Pada 2018, meski tensinya agak menurun, tetapi pilkadanya masih terus berjalan dan kita tetap harus bersiap. Misalnya, bibit-bibit itu, stigma-stigma, dan benturan antarkelompok sudah mulai bisa kita baca dan temukan di Sumatra Utara. Jadi kalau Pilkada itu head to head, sangat kompetitif, maka ruang-ruang kompetisi yang menggunakan cara-cara ilegal lebih cenderung untuk muncul.
Bagaimana dengan Sumatera Utara? Apa indikasinya?
Misalnya bicara mengenai suku, bahasa-bahasa “Melayu menolak pendatang” itu sudah mulai ditemukan. Kemudian tagline, “Kalau ini terpilih, maka kelompok agama ini yang akan mendominasi”. Semestinya, politik itu memang soal identitas karena memperjuangkan kepentingan kelompok, tapi yang sifatnya ideologis melalui cara-cara yang demokratis dan anti-kekerasan. Kalau bahasa dalam demokrasi sudah mulai mengalienasi, meminggirkan, menyingkirkan kelompok lain, apalagi jika ditambah dengan ujaran-ujaran kebencian atau provokatif, maka itu yang berbahaya.
Mengapa hal itu masih dipakai? Apakah memang itu kebiasaan, atau strategi yang masuk akal dalam teori politik, atau memang ini bentuk frustasi?
Salah satunya karena memang calon ini tidak mengakar secara sosial. Jadi ketika dia tidak punya basis sosial yang kuat, lahir dari sebuah proses rekrutmen yang instan karena mengandalkan modal dan juga jaringan elite, maka dia siap menang dan tidak siap kalah. Jadi yang digunakan adalah cara-cara yang sifatnya ilegal, dan bagaimana memicu sentimen dengan cepat sehingga ada emosi pemilih yang bisa dia kendalikan.
Sekarang banyak yang mengatakan kita berada di tengah post-truth era, fakta tidak lebih penting daripada emosional seseorang untuk membuat sebuah keputusan atau kebijakan. Yang paling mudah mempengaruhi emosi seseorang, yaitu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Jadi ketika calon tidak mempunyai basis sosial, tidak mengakar secara kultural, tidak berinvestasi sosial sejak awal pencalonan, lalu maju karena faktor elit dan modal maka yang dipakai adalah sentimen SARA.
Kalau kita lihat ini pasti berasal dari elitenya, dari calonnya, dan dari tim suksesnya. Apakah masyarakat kita sudah mempunyai antibiotik atau kekebalan yang baik terhadap godaan-godaan post-truth tadi?
Post-truth ini adalah fenomena global yang kemudian menguat jika kita melihat di Pilpres Amerika Serikat. Tetapi di Indonesia, ini digunakan dan diperburuk oleh perilaku elite yang tadi. Dia lahir dari sebuah proses rekrutmen yang tidak demokratis, mengandalkan modal, jaringan elite, tidak mengakar secara sosial, lalu mentalitasnya yang siap menang dan tidak siap kalah. Ini kemudian yang membuat masyarakat dibangun sentimen dengan pendekatan yang dulu memecah-belah kita.
Ini sudah mulai kelihatan mempunyai dampak, betulkah?
Iya, dan ini berkelindan antara pilkada kemudian beririsan dengan proses persiapan Pilpres 2019.
Apakah Anda melihat masyarakat kita gampang terbawa dengan isu-isu seperti itu atau punya kekebalan yang baik?
Ruang-ruang publik kita diisi oleh dikotomi politik yang dikuatkan oleh para eliet, kemudian media juga ikut berkontribusi.
Itu karena juga menghasilkan news.
Betul, itu news yang luar biasa. Jadi ada kontribusi juga yang harus kita akui, sehingga ruang-ruang publik kita kurang menghadirkan situasi positif yang bisa membuat pemilih kita bisa lebih berpikir rasional. Yang tadinya sudah ada fenomena global bahwa emosi itu disentil dengan sentimen yang mengandung SARA dan provokasi, politik identitas, kemudian ruang-ruang publik kita juga tidak mendapatkan alternatif informasi yang lebih positif.
Kalau dilihat dari jumlah calon kepala daerah yang mencapai puluhan, dan calon legislatif yang jumlahnya ratusan, apakah perkembangannya makin hari makin baik atau makin buruk dari segi kualitas, dan sebagainya?
Secara prosedural, pelaksanaan pemilu kita membaik. Prosedur demokrasi Indonesia menjadi rujukan dunia soal bagaimana kita mengorganisir pemilu. Namun problem besar kita adalah hasil pemilu. Ternyata hasil pemilu belum berkontribusi terhadap ekspektasi publik, misalnya terhadap peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, kita masih mempunyai masalah dengan kualitas kandidat.
Jadi isu yang muncul sekarang adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha untuk melarang mantan napi koruptor untuk maju. Itu karena salah satunya terkait beberapa calon kepala daerah terpilih adalah mantan napi korupsi, kemudian orang yang mempunyai masalah hukum tetap menjadi kandidat.
Pada 2018 sedihnya sudah ada delapan kandidat kepala daerah yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Delapan kepala daerah ini ada beberapa yang calon gubernur, seperti di Sulawesi Tenggara dan Lampung. Jadi kalau ditanya prosedur kita oke, tapi kita masih mempunyai problem di kualitas kandidat dan kualitas hasil dari keterpilihan kepala daerah.
Anda mengatakan bahwa KPU mencoba membuat terobosan untuk mencegah korupsi dengan adanya intervensi-intervensi prosedural. Mengapa harus menunggu inisiatif KPU membuat terobosan peraturan dibanding dengan kita serahkan saja ke partai politik karena mereka seharusnya bertugas memproduksi calon-calon yang baik?
Kalau menunggu partai politik nyatanya situasi itu tidak tersedia saat ini. Dulu sewaktu pembahasan Undang-Undang (UU) tentang Pemilu, suara masyarakat sangat kuat meminta yang statusnya tersangka atau mantan napi korupsi jangan dijadikan calon. Partai politik adalah gudangnya kaderisasi dan rekrutmen politik. Ternyata itu seperti membentur tembok.
Jadi ketika situasi itu tengah kita hadapi maka semua pihak harus mengambil peran. Sekarang KPU sedang mengambil peran mengatur agar para mantan napi korupsi tersebut tidak dapat menjadi calon. Karena kita tidak boleh membiarkan pemilih mempunyai potensi untuk memilih calon-calon yang bermasalah. Kalau ditanya, bagaimana dengan partai politik? Kuncinya memang di partai politik. Jadi problem terbesar pemilu dan demokrasi kita adalah partai politik yang makin menjauh dari fungsinya. Pendidikan politik belum dilakukan secara optimal. Kaderisasi bisa dikatakan mandek. Contoh variabel ukurnya adalah makin banyak calon tunggal. Pada 2018 dari 171 daerah yang Pilkada, 16 daerah calon tunggal. Ini merupakan refleksi dari mandeknya kaderisasi.
Apakah ini mungkin juga karena oligarki makin kuat?
Oligarki yang makin kuat yang notabene kendali modalnya yang semakin dominan. Jadi ketika situasi itu yang kita hadapi maka semua aktor negara mempunyai tanggung jawab untuk mengambil peran. KPU mengambil perannya ketika misalnya partai politik makin jauh dari fungsinya.
Tapi ini kemudian banyak diprotes oleh politisi karena menabrak UU yang ada. UU Pemilu dan UU Pilkada kita tidak mengatakan itu, bahkan boleh saja asal kamu menyatakan kamu mantan narapidana korupsi. Ini adalah sesuatu yang baik tapi melanggar UU. Bagaimana kalau alasannya seperti itu?
KPU itu berdiri dalam perspektif baru. Jadi kalau argumen legalistik formal memang akan seperti itu. Namun kalau bicara mengenai perspektif hukum, masing-masing pihak bisa mempunyai sudut pandang dalam memaknai hukum. Tinggal sekarang apakah kita mau mendorong langkah ini untuk kemaslahatan. Kalau argumen hukum saya yakin itu bisa dicari. Yang sulit dicari adalah political will atau itikad baik atau kemauan untuk melakukan perubahan.
Apakah ini berarti menolak dengan alasan hukum itu karena tidak ada political will dari pemangku kebijakan?
Saya meyakini begitu. Kalau political will ada, maka aturan itu semestinya pada level UU sudah tersedia. Sekarang situasi kita sangat luar biasa, 171 daerah Pilkada, delapan kepala daerah di-OTT oleh KPK. Lalu kita akan menghadapi Pemilu legislatif. Persoalan yang sama bukan tidak mungkin juga akan terjadi.
Dalam menghadapi situasi yang luar biasa, maka langkah-langkahnya juga harus luar biasa. KPU mengambil perannya, KPK juga mengambil perannya melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Dan kita masyarakat sipil memberi perspektif baru pada pemilih agar betul-betul tidak salah pilih pemimpin.
Apakah memungkinkan niat baik KPU bisa terealisasi melihat situasi dan kekuatan politik sekarang. Misalnya, melarang napi koruptor untuk ikut dalam pilkada atau pemilu legislatif. Juga memaksakan semua calon legislatuf harus membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Apakah menurut Anda ide-ide ini akan mungkin terwujud dengan kondisi peta politik dan format politik sekarang?
Saya kira terwujud atau tidak adalah gol yang harus kita wujudkan bersama. Masyarakat sipil harus berada di belakang upaya-upaya ini. Kami mengharap betul media membangun diskursus-diskursus di tengah publik kita untuk memberikan dukungan kepada langkah-langkah progresif seperti yang dilakukan oleh KPU.
Ketika bicara produk legislasi UU, kita mengetahui UU Pemilu kita selalu didesain untuk menyisakan cela bagi terjadinya manipulasi. Ketika KPU hadir dengan pilihan-pilihan progresif, maka masyarakat sipil wajib berada di belakang institusi dan aktor-aktor dengan tawaran progresif itu.
Apakah ini bisa efektif mencegah terjadinya korupsi, serta membuat kepala daerah dan anggota parlemen kita tidak korupsi?
Korupsi adalah masalah luar biasa bangsa kita saat ini. Kalau kita bisa urai secara sederhana, tiga masalah besar bangsa kita adalah pertama, korupsi. Kedua, narkoba. Ketiga, kejahatan terhadap anak yang angkanya terus naik.
Dalam konteks korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, semua pihak harus ambil peran. Peran KPU adalah sebagai regulator pemilu, kontribusinya di situ. Ibu dari korupsi konon katanya adalah korupsi politik. Untuk mencegah korupsi politik harus dari semua lini kita kawal. Dari reformasi partai politiknya kita lakukan.
Jadi ketika ada riset yang mengatakan partai politik korup karena mereka mempunyai masalah pendanaan, lalu lahirlah skema dengan memperkuat public funding atau skema dana negara untuk partai politik, sehingga dengan meningkatnya dana negara untuk partai politik yang berasal dari APBN/APBD bisa mengimbangi dominasi pemodal.
Jadi lebih independen partai politik tersebut.
Betul. Jadi yang selama ini partai dikendalikan oleh para oligarki, para pemilik modal, sekarang para kader-kader potensial lebih mempunyai posisi tawar karena ada kontribusi dari dana publik di sana yang berasal dari dana negara. Itu salah satu tawaran yang kita sampaikan.
Sekarang proses elektoral itu bagaimana menjaga orang-orang yang nanti akan menjadi pemproduksi UU, anggaran, pengawasan adalah orang-orang yang dari awal sudah bisa kita ukur komitmen anti korupsinya dengan alat yang sudah kita punya. Kejujuran dan komitmen anti korupsi salah satunya diukur dengan menyampaikan laporan harta kekayaan.
Apa yang Anda bayangkan dari pilkada dan pemilu kali ini. Apakah Anda mempunyai optimisme yang lebih besar dari beberapa tahun yang lalu?
Optimisme tidak boleh mati, harus selalu dibangun. Apa pun yang terjadi dengan perjalanan bangsa kita, kita tidak boleh kehilangan kepercayaan pada demokrasi. Itu karena seberapa besar tantangan demokrasi yang kita hadapi sekarang, demokrasi masih menawarkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan oligarki dan otoritarian.
Kalau kita tidak bisa memelihara demokrasi ini, maka ancamannya adalah otoritarian dan oligarki akan kembali. Ini yang membuat kita harus tetap waspada, harus tetap menyiapkan diri, dan harus bergandengan tangan sesama masyarakat sipil, media, dan aktor kepentingan untuk memproteksi demokrasi kita agar tidak mengalienasi kelompok minoritas, tidak menjauhkan kelompok-kelompok marjinal dari pusaran kompetisi, menjaga inklusivitas, menjaga kesetaraan, dan yang terpenting menjaga demokrasi adalah menjaga ke-Indonesia-an kita.
*Tulisan ini merupakan kerja sama Perspektif Baru dengan Harian Jogja, sudah dimuat di koran Harian Jogja, 28 Mei 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Yayasan Perspektif Baru
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement

Giliran Jogja! Event Seru Supermusic Superstar Intimate Session Janji Hadirkan Morfem
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement