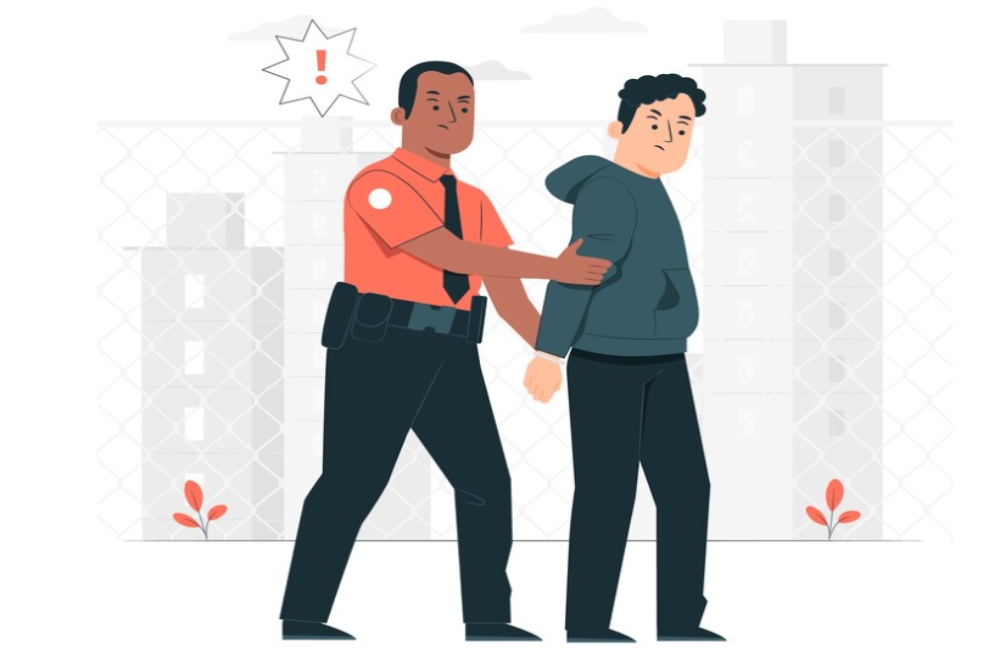Advertisement
KDRT: Konflik atau kekerasan ?
 Ester Lianawati - Ist.
Ester Lianawati - Ist.
Advertisement
Kesigapan polisi dalam melayani pengaduan korban dan peningkatan jumlah kasus yang ditindaklanjuti merupakan kemajuan yang perlu dicatat dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Di sisi lain, rekonsiliasi korban dan pelaku masih menjadi pilihan utama penegak hukum. Korban masih rentan untuk balik diposisikan sebagai pelaku. Kecuali untuk kekerasan berat, pelaku masih cenderung lepas dari hukuman.
Advertisement
Bulan ini 14 tahun sudah sejak Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) disahkan 22 September 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Mengapa masalah-masalah yang sama belum teratasi ?
Serge Moscovici, bapak psikologi sosial Eropa mengusulkan untuk melihat persoalan-persoalan dalam masyarakat dengan menggunakan kerangka representasi sosial. Representasi sosial dapat diartikan sebagai imaji mental, gambaran dan kepercayaan-kepercayaan yang telah terinternalisasi dalam masyarakat. Menurut dia, tiap individu dalam suatu masyarakat akan mengacu kepada representasi sosial yang sudah ada ketika berhadapan dengan ide yang masih asing sebelum akhirnya representasi baru akan lahir dalam masyarakat tersebut.
Dalam proses pembentukan sebuah representasi baru, masyarakat akan mengacu kepada representasi-representasi lama yang sudah mengakar. Itu pula yang kita lakukan, bahwa kita memaknai KDRT dengan mengacu kepada konsep lama, khususnya dengan konflik rumah tangga, sebagai konsep terdekat dengan KDRT.
KDRT adalah konflik dalam rumah tangga dengan penggunaan kekerasan di dalamnya. Demikian kurang lebih pemaknaan masyarakat kita terhadap KDRT. Tampak bahwa KDRT tetap dimaknai sebagai konflik rumah tangga meski diberikan penekanan adanya unsur kekerasan di dalamnya. Di sini kita dapati representasi yang bersifat kait-mengait (interlocked) antara KDRT, konsep baru, dengan konflik rumah tangga, konsep lama. Kita meletakkan konsep baru dalam kerangka konsep lama.
Representasi ini pada kelompok penegak hukum diperkuat oleh cukup banyaknya pengaduan yang masuk yang memang “hanya” berupa konflik-konflik rumah tangga. Menjadi pertanyaan, mengapa banyak yang melaporkan diri sebagai korban kekerasan sementara yang dialami sekadar konflik rumah tangga ?
Tampaknya representasi yang kita miliki mengenai KDRT tidak hanya bersifat kait-mengkait tetapi juga tercampur aduk dengan konflik rumah tangga. Tidak hanya memandang KDRT sebagai konflik, kita juga menganggap konflik dalam rumah tangga sebagai kekerasan ketika ia menimbulkan penderitaan fisik atau psikis.
Ada dua masalah akibat pemahaman ini. Pertama, konflik dapat saja berakhir buruk dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik. Misalnya pertengkaran hebat yang terhenti dengan sebuah tamparan akibat hilangnya penguasaan diri. Tamparan yang terjadi saat pertengkaran tidak selalu menandakan ada kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi tamparan adalah tindak kekerasan. Pihak yang dikenai tindakan ini dapat melaporkan diri sebagai korban KDRT meski yang terjadi sesungguhnya adalah konflik.
Kedua, semua konflik dapat dimaknai secara subjektif sebagai membawa “penderitaan”. Akibatnya semua urusan dalam rumah tangga dapat dilaporkan dengan berlabelkan KDRT. Perselingkuhan, kebohongan suami mengenai masa lalunya dengan perempuan lain, dan persoalan-persoalan lain yang sifatnya sangat personal. Bahkan bukankah masing-masing pasangan berpotensi melukai perasaan satu sama lain ketika sedang bertengkar? Di sini kita dapat melihat representasi yang bersifat tercampur aduk antara KDRT dan konflik membuka celah untuk interpretasi subjektif. Masing-masing pihak dapat saling melaporkan.
Karena menganggap KDRT sebagai konflik, penegak hukum berusaha mendamaikan korban dan pelaku. Polisi beralih peran menjadi konselor perkawinan. Hakim pun menanyakan kemungkinan korban dan pelaku berdamai sekali pun proses pengadilan sudah mencapai tahap putusan. Selain itu, dalam konflik biasanya suami dan istri keduanya sedikit banyak mengambil peranan. Dengan menganggap KDRT sebagai konflik, penegak hukum melihat korban berkontribusi dalam terjadinya kekerasan.
Pandangan ini berisiko memosisikan korban sebagai pelaku. Terkait dengan hal ini, karena menganggap konflik sebagai KDRT, tiap orang dapat menamakan diri sebagai korban dan menuduh yang lain sebagai pelaku. Pihak yang menjadi korban sebenarnya rentan untuk dipidanakan karena pelaku dapat leluasa memutarbalikkan keadaan.
Siklus Kekerasan
Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kekacauan ini? Terlebih dahulu kita harus memisahkan representasi yang kait-mengait dan tercampur aduk antara konflik dan kekerasan. Dengan perkataan lain, kita harus belajar membedakan konflik dan kekerasan.
Ada relasi kuasa dalam kekerasan, salah satu pasangan mendominasi, mengontrol, menempatkan korbannya dalam posisi subordinat. Korban merasa terancam dan hidup dalam suasana tercekam. Ia seperti berjalan di atas telur, khawatir kalau-kalau berbuat kesalahan yang dapat menimbulkan kemarahan pelaku. Dengan makian dan penghinaan yang konstan, pelaku mencuci otak korban dan menciptakan ketergantungan emosional. Korban meyakini dirinya bukan siapa-siapa tanpa pelaku dan kelebihannya hanya satu: memancing pelaku bertindak kasar.
Jangan bayangkan tidak pernah ada kebahagiaan dalam rumah tangga ini. Momen-momen manis sesekali tercipta, dan ini memberi harapan kepada korban bahwa pelaku dapat berubah. Momen ini hanya sementara, korban harus siap dengan kembalinya tahap ketegangan yang diakhiri dengan tindak kekerasan. Pola ini berulang membentuk siklus kekerasan.
Polisi ketika menerima korban sebaiknya menanyakan apakah telah terjadi kekerasan-kekerasan sebelumnya, fisik maupun psikologis. Ajukan pertanyaan sekonkret mungkin karena masih ada korban yang belum paham bahwa apa yang ia alami adalah kekerasan terutama dalam hal kekerasan psikis.
Penegak hukum juga harus bersikap tegas kepada pihak yang melakukan tindak kekerasan. Tindak kekerasan, seringan apa pun dan meski terjadi hanya sekali karena situasi konflik memanas, tidak dapat ditoleransi. Hilangnya kontrol diri bukanlah pembenaran, demikian pula dengan provokasi korban. Jangan berusaha mencari “peran” korban dalam kekerasan. Pelaku adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas tindakannya.
Tanggung jawab korban adalah untuk keluar dari relasi kekerasan. “Ia sebenarnya baik jika tidak sedang kasar.” Demikian ucapan korban yang masih dalam tahap penyangkalan. Psikolog, pendamping ataupun penegak hukum dapat membantu memberikan penyadaran kepada korban bahwa persoalan yang terjadi dalam rumah tangganya adalah kekerasan dan bukan konflik. Pengakuan akan statusnya sebagai korban adalah langkah awal pemulihan.
Tetapi hendaknya kita tidak pula menciptakan masyarakat “korban”, ketika individu di dalamnya begitu mudah mengklaim diri sebagai korban hanya karena merasa sakit hati dan terluka. Tempatkan semua pada proporsinya. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah konflik. Namun tidak semua konflik dapat kita anggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga.
*Penulis adalah psikolog, sedang menempuh program doktoral psikologi di Université de Rouen, Prancis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Kompak Ambil Formulir Pendaftaran di Partai Golkar
Advertisement

Berikut Rangkaian Program Pilihan Keluarga Indonesia Paling di Hati, Hanya di MNCTV
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement